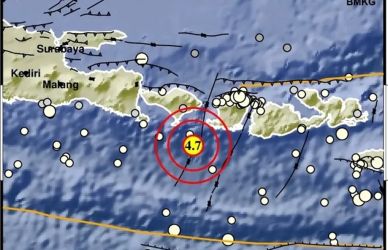Membubarkan Partai Coklat

PARTAI Coklat dimaknai oleh salah seorang politisi PDI Perjuangan sebagai sekelompok oknum birokrasi baik sipil bersenjata maupun sipil biasa yang mengendalikan elektabilitas di sejumlah kontestasi pilkada. Realitas itu mungkin dirasakan sekalipun tak cukup keberanian publik untuk membawa ke meja hijau pengadilan pemilu.
Dalam dua sampel yang dikemukakan, yaitu kasus Pilkada Jateng dan Sumut mengindikasikan terjadinya mobilisasi senyap dan terang-terangan pada paslon tertentu. Bila benar, tentu saja melukai demokrasi. Kegagalan demokrasi di sejumlah negara karena birokrasi lalai menjadi pengawal, justru menjadi patologi dalam praktik ketidaknetralan.
Demokrasi berkembang di Jepang karena kaum samurai (birokrasi) menjadi pengawalnya, demikian pula posisi kaum aristokrat, akademisi, dan politisi di Perancis, India dan Jerman (Boediono, 2007). Para profesional menempatkan jiwa kesatrianya sebagai pengawal negara, bukan anjing penyalak _(underdog)_ penguasa yang relatif setiap periodik.
Untuk meyakinkan itu, bisa dilihat fungsi negara. Fungsi _eksternal security_ dijalankan oleh tentara. Fungsi _internal security_ dilakukan oleh polisi. Fungsi peradilan ditegakkan oleh _justice court._ Fungsi melindungi kebebasan dilaksanakan oleh otoritas sipil. Sedangkan fungsi menciptakan kesejahteraan dijalankan oleh birokrasi sipil (Mulyadi, 2024).
Dengan pemahaman itu, polisi sekaligus bagian dari birokrasi punya fungsi yang khas atas nama negara, bukan atas nama penguasa. Bilapun atas nama pemerintah, Ia menandakan bagian dari unsur negara. Artinya tindakan polisi dan birokrasi adalah untuk dan atas nama negara, bukan _on behalf_ penguasa. Inilah maklumat negara hukum, bukan negara kekuasaan sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) konstitusi '45.
Bila hari ini terjadi pengangkangan atas fungsi ideal dan normatif, sejogjanya perlu dilakukan langkah strategis guna membubarkan aktivitas partai coklat sebagai kelompok ilegal yang leluasa melakukan _cawe-cawe_ atas kepentingan tertentu. Tanpa pertaubatan, hal ini dapat menjadi preseden negatif bagi kelangsungan dan stabilitas demokrasi di masa mendatang.
Solusi terbaik hanya dengan mengembalikan mekanisme demokrasi menjadi pemilu tak langsung _(indirect election)._ Mekanisme ini dengan sendirinya menghentikan langkah partai coklat turut serta bergelimang dosa dalam kontestasi pemilu dan pilkada. Bila berat mengubah pasal 6A ayat (1), setidaknya lebih mudah menerjemahkan pasal 18 ayat (4), kepala daerah cukup dipilih DPRD.
Dengan perubahan itu, partai cokelat praktis hanya akan menjadi penonton, dan kembali ke _khittoh_ nya, pengawal demokrasi, bukan _underdog_ penguasa. Perubahan itu sekaligus mampu mengurangi praktek politik uang, memperkuat posisi partai yang selama ini hanya menjadi _event organizer._
Perubahan mekanisme pun dapat mengurangi potensi konflik sebagai bahaya laten yang hanya menguntungkan partai coklat. Lebih dari itu ongkos demokrasi dapat lebih efisien tanpa mengurangi nilai demokrasi. Faktanya mekanisme representasi itu jauh lebih mendekati sila keempat Pancasila, bahkan telah dipraktikkan selama 60 tahun (1945-2005).
Tekanan terhadap ongkos demokrasi yang mahal itu dapat dialokasikan untuk makan bergizi gratis. Biaya mekanisme demokrasi yang penuh risiko, panjang, melelahkan, dan menelan biaya hampir Rp 150 triliun (pemilu dan pilkada) dapat menghemat kantong negara yang cekak akibat korupsi dihampir semua cabang kekuasaan _(trias koruptika)._
Andai negara dapat menangkap lima pelaku tambang ilegal dengan asumsi perorang menilep Rp 271 triliun. Artinya, negara tak perlu kesulitan mencari Rp 1.355 triliun untuk menutup hutang negara, gaji guru dan makan siang gratis. Sekali lagi, negara tak perlu mengubah sistem politik demokrasi, cukup mengembalikan mekanisme demokrasi di tingkat lokal dari langsung ke tidak langsung (revisi UU Pilkada).
Lewat terobosan itu, mekanisme demokrasi dengan sendirinya akan memaksa partai coklat membubarkan diri. Harus diakui, bahwa selama praktik demokrasi langsung 20 tahun (2004-2024), partai cokelatlah yang paling diuntungkan, dimana pertukaran modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik (meminjam istilah Pierre Bourdieu), telah mengubah idealitas demokrasi menjadi brutal dan tak bermoral.(***)
*) Penulis merupakan Guru Besar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Olahraga | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Olahraga | 9 jam yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 1 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu