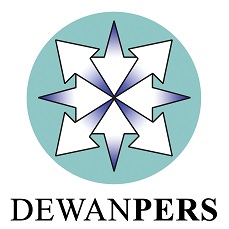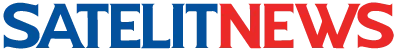Populisme dan Lunturnya Pamor Birokrasi

DI Bumi Pasundan yang sarat makna dan sejarah, muncul sosok yang dielu-elukan. Ia bukan sekedar menjual prinsip, juga pesona. Seakan Gunung Tangkuban Perahu sedang mengirim pesan lewat para leluhur tentang masa depan kepemimpinan di kelak hari. KDM (Kang Dedi Mulyadi) tampil tanpa ragu dihadapan rakyatnya. Bukan sebagai negarawan dengan visi etik dan tanggung jawab institusional, tapi aktor populis yang disindir teman seprofesinya, gubernur konten. Ia menampik, itu efisiensi iklan yang justru menghemat.
Ia menakar gelisah rakyatnya tanpa jaminan bebas sepenuhnya dari lingkaran struktural kemiskinan dan ketidakadilan. KDM bukan semata figur publik yang merakyat, tapi simbol kekuasaan yang menanggalkan kedalaman, plus narasi personal yang meyakinkan. Ia tampil sebagai narator dari kisah-kisah kemiskinan, penderitaan, dan keputusasaan kaum alit. Mencoba membongkar akar sistemik yang melanggengkan penderitaan, seraya membingkainya lewat kemasan konten visual, empati instan, dan dramaturgi elektoral.
Populisme adalah wajah modern politik teatrikal. Kepemimpinan dikonstruksi bukan lewat dialektika kritis. Apalagi gagasan besar tentang keadilan sosial, melainkan simbolisme, narasi, dan hubungan personal tanpa perantara institusi demokrasi yang butuh dialog (policy without politics). Tak heran bila sebagian anggota DPRD walk out (Tempo, 2025).
Kepemimpinan populis melampaui batas etika dan estetika. Membaurkan keduanya menjadi performa memikat, namun terkesan dangkal. Fenomena semacam itu bukan baru sekarang, publik pernah kapok oleh kenekatan kepemimpinan gorong-gorong yang kini menjelma menjadi goreng-goreng. Di balik senyuman, pelukan, dan kompensasi recehan kaum populis terdapat jebakan berbahaya. Penggiringan kesadaran kolektif kedalam ilusi; bahwa perubahan bisa hadir tanpa struktur, tanpa kebijakan, tanpa reformasi, dan tanpa diskusi. Dengan seperangkat kamera dan empati publik, KDM cukup mengobati infeksi sosial yang diwariskan sejarah, dan gagalnya institusi pemerintah dimasa lalu.
Dalam filsafat politik, kepemimpinan adalah amanah, bukan panggung popularitas. Ia mensyaratkan logos (rasionalitas), ethos (integritas), dan pathos (kepedulian autentik). Seorang pemimpin yang hanya mengandalkan pathos tanpa logos dan ethos, dapat menjelma menjadi penyair tanpa hikmah. Menghibur, namun tak menyembuhkan luka peradaban.
Etika publik menuntut pemimpin membebaskan rakyat dari ketergantungan figur. Bukan merawat patronase dalam format relasi pengasuh-dikasihi yang memperdaya. Relasi ini mencipta hubungan antara Menak dengan Santana, antara Raja dengan Rakyat. Maka, ketika KDM menampilkan dirinya seakan Raja yang hadir di tengah kerumunan, publik mesti bertanya: apakah Ia sedang membangun sistem, ataukah sekadar menampilkan empati bagi investasi politik di 2029? Faktanya, kepemimpinan populis dalam 10 tahun terakhir memberi kita mimpi buruk, mengaburkan batas antara empati dan eksploitasi.
Kaum populis cenderung mengangkat derita dan aksi instan sebagai tontonan. Bukan panggilan membongkar struktur ketimpangan. Ia memperkuat ketergantungan emosional antara rakyat dan figur. Bukan membangkitkan kesadaran kritis membangun institusi yang adil. Di titik ini, kita perlu kembali pada panggilan etik. Pemimpin bukanlah penyelamat personal, melainkan penggerak perubahan struktural. Rakyat bukan objek belas kasih, melainkan subjek politik berdaulat. Dan bahwa penderitaan sosial tak boleh dijadikan ladang pencitraan, tapi medan perjuangan memenuhi keadilan.
Tentu publik perlu awas. Dalam beberapa kasus populisme mampu mengubah kekuasaan menjadi anti-kritik, anti-struktur, dan anti-pembebasan. Puja-puji jutaan followers dapat membutakan. Seakan pandangannya adalah kehendak rakyat (der wahre wille des volkes). Tak sedikit pasca tak berkuasa disangka penipu, psikopat dan amoral.
Di sisi pemerintahan modern, tumbuh birokrasi sebagai pilar rasionalitas yang dirancang berdasarkan kompetensi, hierarki, profesionalitas, dan objektivitas. Satu tatanan yang menurut Weber disebut rasionalitas instrumental (1922). Dalam kerangka itu meritokrasi menjadi tulang punggung birokrasi. Namun, ketika figur hadir dalam lanskap kepemimpinan lokal dengan gaya populis, muncul dilema epistemik dan etis antara birokrasi berbasis sistem dan prosedur, ataukah kepemimpinan populis berbasis ikatan emosional dan improvisasi personal.
Populisme mengancam desaign thinking birokrasi yang selama ini jadi acuan. Perencanaan dan penganggaran mesti diinstal ulang, atau mungkin dirombak total. Itu membuat birokrasi lemas dan cemas menuju tahun emas. Konsekuensinya tak cuma hukum, juga mindset yang berhadapan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria dari atas.
Positifnya, populisme yang komunikatif dan lugas mampu melenturkan mesin birokrasi yang dipersepsikan kaku, dingin, dan tak terjangkau. Kaum populis dapat mengubah wajah mesin birokrasi tua menjadi entitas humanis. Hal yang jarang dicapai oleh birokrasi traditional. Kepemimpinan populis menembus jalur lambat birokrasi dengan mengangkangi cara kerjanya yang rabun. KDM dan aksi empatiknya seakan mendorong birokrasi ke sumber masalah yang sering macet. Ini auto-koreksi yang kerap terjadi dalam patologi birokrasi.
Dalam konteks layanan publik, KDM menghidupkan kembali semangat pelayanan dalam arti sesungguhnya. Ia menunjukkan seorang pejabat publik bukan sekadar pengelola sistem, tapi pelayan yang hadir di tengah masyarakat. Memberi contoh agar tak bersembunyi di balik meja, tapi berkubang lumpur di tengah sawah. Minusnya, kepemimpinan populis menciptakan jalur non-formal di luar sistem birokrasi. Ketika keputusan diambil berdasarkan keinginan pemimpin dan bukan prosedur baku, birokrasi kehilangan orientasi sistemiknya. Mereka yang sehari-hari bekerja berdasarkan kompetensi dan capaian kinerja, tunduk pada selera personal pemimpin populis.
Birokrasi yang terpapar pemimpin populisme sangat rentan terjebak budaya patronase. Birokrat cenderung membangun loyalitas pada sosok, bukan sistem. Birokrasi bekerja bukan karena tanggung jawab jabatan, tapi demi mendapatkan pengakuan dan afiliasi pemimpin. Pada jarak jauh merusak impersonalitas yang menjadi prinsip birokrasi.
Lebih dari itu, bila tindakan spontan dan respons personal pemimpin lebih diapresiasi daripada prosedur formal birokrasi, maka legitimasi birokrasi kehilangan pamor. Publik lebih percaya pada aksi langsung daripada keputusan kolektif. Ini menciptakan ketergantungan pada figur, bukan institusi. Dalam perspektif etis tentu saja menghambat tumbuhnya kepercayaan publik pada sistem. Eksesnya, yang menjadi ukuran keberhasilan bukan capaian kebijakan berbasis data, melainkan gestur simbolik dan narasi emosional. Jokowi dan Ahok sedikit contoh yang fokus pada narasi kemiskinan dan penyelamatan individual, tapi mengalihkan perhatian publik dari evaluasi berbasis indikator kinerja.
Padahal, birokrasi terbiasa bekerja lewat standar objektif dan terukur. Bukan persepsi publik, apalagi popularitas media sosial. Fenomena KDM bukan sekadar gaya personal, tapi refleksi benturan paradigmatik antara politik afeksi dan institusi. Ia membangkitkan memori kepemimpinan blusukan di tengah impersonalitas birokrasi modern.
Populisme mengancam disiplin birokrasi yang menjadi fondasi tata kelola pemerintahan. Dalam perspektif etika politik, kepemimpinan ideal bukan menonjolkan diri di atas sistem, tapi memperkuat sistem agar melayani secara adil dan berkelanjutan. Mereka membangun institusi, bukan memoles diri seperti badut di tempat sirkus.
Agar tak mengulang kesalahan yang sama, penting mengingatkan bahwa tipelogi kepemimpinan populis sebaiknya mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem, bukan figur semata. Terlepas mayoritas masyarakat tak cukup terdidik. Mereka lebih suka dipandu oleh narasi-emosional lewat gawai ketimbang rasional-sistemik.
Alarm ini tentu bukan saja bagi publik. Lebih khusus birokrasi yang lambat laun kehilangan signifikansi, bahkan tenggelam oleh romantisme kepemimpinan populisme. Mungkin patut direnungkan kritik Ernest Geliner (1969), ein gespenst geht um in der welt der populismus (seekor hantu sedang mengancam dunia, populisme namanya).(*)
*) Penulis merupakan Guru Besar Bidang Politik Pemerintahan (Polpem) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Nasional | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Galeri | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu