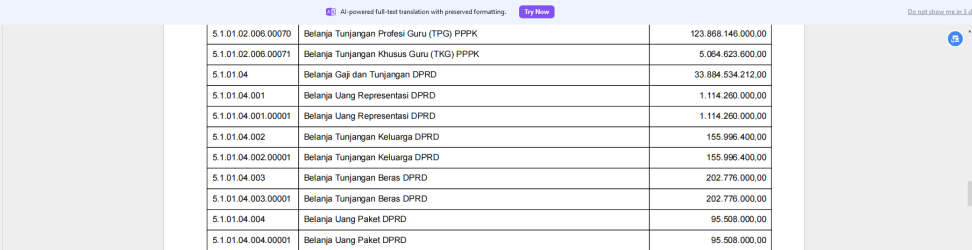Meminimalisir Kelemahan Dipilih DPRD

POLEMIK mekanisme pemilihan kepala daerah menggema ulang. Kali ini dimulai dari pimpinan tertinggi, Presiden Prabowo Subianto di depan Munas Partai Golkar. Ini tentu menggembirakan, sebab dimulai dari atas, bukan dari bawah. Biasanya, kemauan arus bawah _(bottom up)_ sulit menemukan kanalisasi dibanding bila ia menjadi kemauan arus atas _(top down)._
Maknanya, polemik perubahan mekanisme itu punya peluang jalan tol, jika saja semua parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sepakat. Soal PDI Perjuangan seingat saya sudah lama insyaf untuk kembali ke mekanisme tak langsung, termasuk perubahan proporsional terbuka ke tertutup untuk pemilihan legislatif di tahun 2029 kelak.
Saya tidak ingin menguliti lagi kelebihan dan kelemahan dipilih langsung dan tak langsung. Sejak 2012 wacana ini telah digulirkan kembali hingga melahirkan Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Pilkada yang memaksa kembali dipilih DPRD. Malangnya, _beleid_ itu hanya bernafas dua bulan ketika Presiden SBY menjegal lewat Perpu Nomor: 1 Tahun 2014 yang mengembalikan ke mekanisme langsung.
Tiga problem utama yang dijadikan argumen pengamat soal kelemahan mekanisme dipilih DPRD (lihat Aroor, Burges, Huber, Kaplan, 2016-2019). Pertama, meningkatnya peluang politik uang ke level elit DPRD. Kedua, terputusnya atau minimnya partisipasi politik masyarakat. Ketiga, hilangnya akses masyarakat secara independen untuk turut mencalonkan diri. Lalu, bagaimana mencarikan solusi soal itu.
*Pertama,* di berbagai diskusi saya sampaikan bahwa pilihan mekanisme langsung atau tidak, potensi politik uang tetap menganga. Kalau biasanya menetes ke lantai _(trickle down effect),_ kini probabilitasnya merembes ke atap _(trickle up effect)._ Karenanya, bukan di situ soalnya, tapi manakah di antara kedua mekanisme tersebut yang dapat diawasi terkait praktik kotor politik uang.
Sejauh ini praktik politik uang sulit diawasi. Kendatipun ada Bawaslu, Panwas, KPU, dan APH, tetap saja praktik politik uang menjadi gejala dominan dalam pilkada, terbuka maupun tersembunyi. Terbuka bisa dikenali lewat spanduk, _kami siap menerima serangan fajar._ Tersembunyi lewat tangan timses dan birokrasi. Bentuknya pun bisa uang dan barang.
Kendati dibawa ke ruang pengadilan, lengkap dengan barang bukti dan saksi, tetap saja tak menghasilkan keadilan memuaskan. Pelakunya melenggang, bahkan dipromosi. Politik uang rasanya telanjang tapi sulit dihentikan dengan menggunakan instrumen hukum. Hal mana membuat politik uang tumbuh subur, bahkan diterima publik dengan sikap permisif.
Bila mekanisme dipilih DPRD, praktuk politik uang relatif mudah diawasi. Setidaknya pemerintah dapat mendesain mekanisme pengawasan dengan melibatkan institusi PPATK, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian secara terstruktur. Pemerintah dapat melacak aliran dana dari 25 s.d. 125 anggota DPRD dibanding mengawasi 250 s.d. 10 juta pemilih yang menanti sejak fajar.
*Kedua,* minimnya partisipasi masyarakat dapat dikecualikan karena telah diwakili DPRD.
Partisipasi masyarakat dalam pilkada langsung 2024 bahkan hanya mencapai 64 persen dibanding Pilkada 2019 sebesar 81 persen (KPU, 2024). Partisipasi politik dalam sistem demokrasi tidak semata pada soal pemberian suara langsung di TPS, juga pelaksanaan dan pengawasan kepala daerah pasca terpilih.
Selama ini, asumsi tak memilih kepala daerah langsung seakan kehilangan hak demokrasi. Faktanya tanpa memilih langsung kepala daerah seperti di Jogja, masyarakat terdidik tak merasa kehilangan hak demokrasi. Perasaan kehilangan hak demokrasi rasanya berlebihan, sebab dengan memilih wakil rakyat sama maknanya menitipkan pilihan rakyat pada wakilnya. Tinggal bagaimana mengontrolnya.
Di Amerika, hak kontrol tetap terbuka. Mekanismenya disiapkan lewat _public recall._ Bila dalam masa tertentu publik ingin mengganti, cukup mengisi formulir persyaratan yang memungkinkan dilakukannya pilkada atau pileg sela oleh _electoral commision_ guna memperoleh calon pengganti antar waktu. Artinya publik tak kehilangan daulat dan hak kontrolnya.
Disitu hak demokrasi rakyat tetap eksis sekalipun sebagian besar terkait legislasi, budgeting, dan kontrol diserahkan ke wakil-wakil yang telah dipilih. Praktik ini perlu dirancang dalam mekanisme baru agar hak _recall_ tidak absolut menjadi milik ketua partai. Praktik ini dapat menjadi penyeimbang sehingga rakyat tetap berdaulat dan mampu mengontrol wakilnya yang tak amanah.
*Ketiga,* hilangnya akses masyarakat untuk terlibat dalam pilkada lewat DPRD dapat diantisipasi dengan memaksa setiap partai melakukan mekanisme konvensi. Praktik ini pernah dilakukan Golkar sehingga kaum profesional, birokrat, artis, akademisi, bahkan kaum populis dapat berkompetisi sebelum disodorkan partai menjadi representasi dalam kontestasi pemilu (2004).
Dengan model itu, akses setiap kandidat kepala daerah terbuka untuk siapa saja. Sikap inklusif partai dapat menarik kader terbaik di dalam dan luar untuk ikut berkontestasi. Tanpa keterbukaan, pola rekrutmen hanya akan bergerak di sekitar elit partai. Inilah salah satu masalah mengapa mekanisme dipilih DPRD ditinggalkan sejak 2005.
Melalui strategi itu, seraya memperbaiki tata kelola parpol di hulu, saya yakin kita mampu meminimalisir kelemahan mekanisme dipilih DPRD. Tentu saja perubahan mekanisme penting difokuskan pada perubahan regulasi pemilu, pilkada, dan parpol. Pemilu terkait pemisahan pengaturan, pilkada berhubungan dengan mekanisme, sedangkan parpol bertalian dengan tata kelola dan mekanisme rekrutmen internal.(*)
Penulis merupakan Guru Besar pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)
Nasional | 2 hari yang lalu
Olahraga | 1 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Pos Tangerang | 1 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu