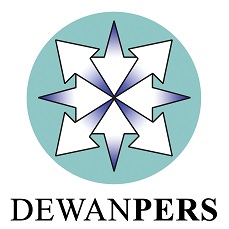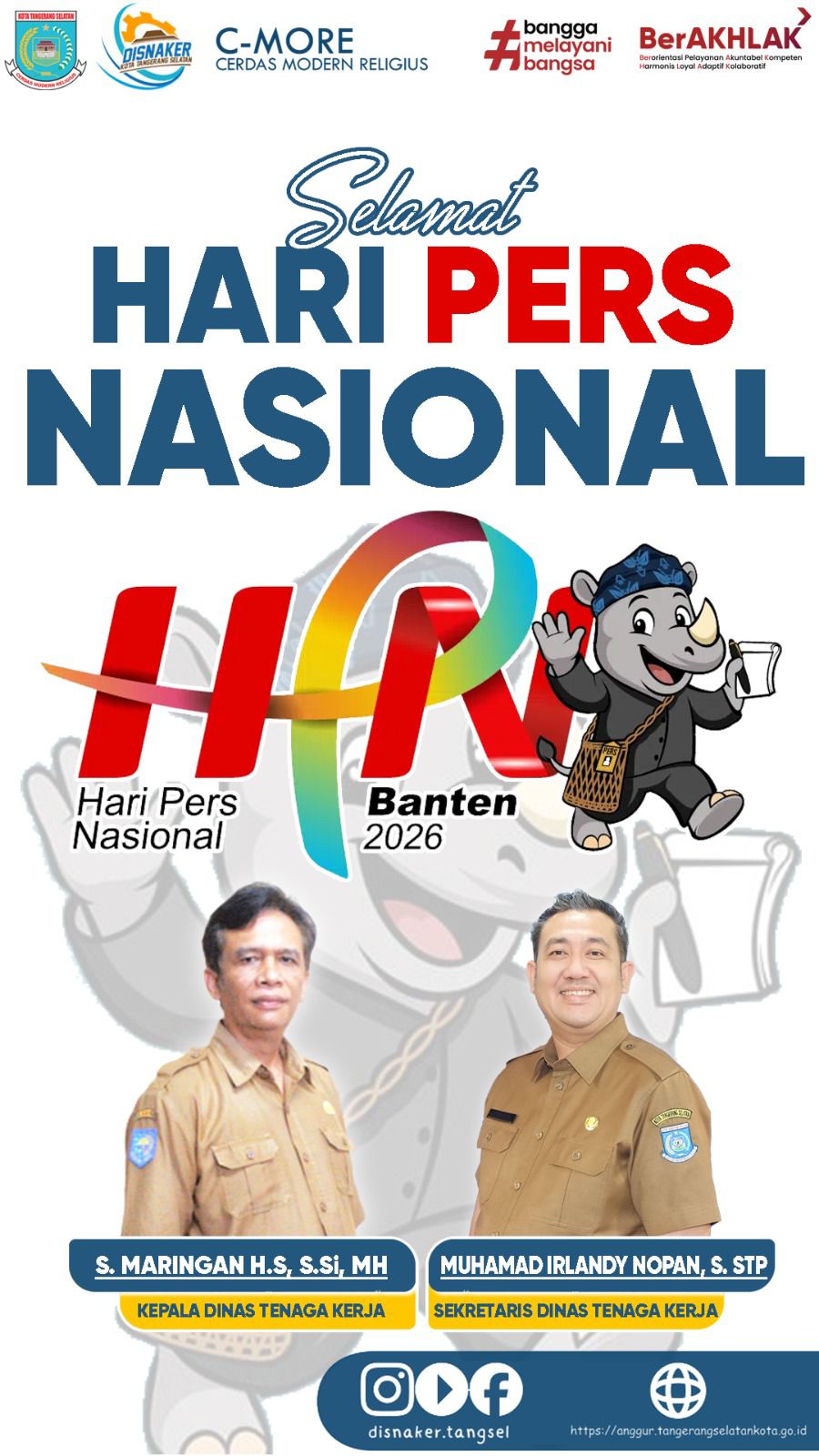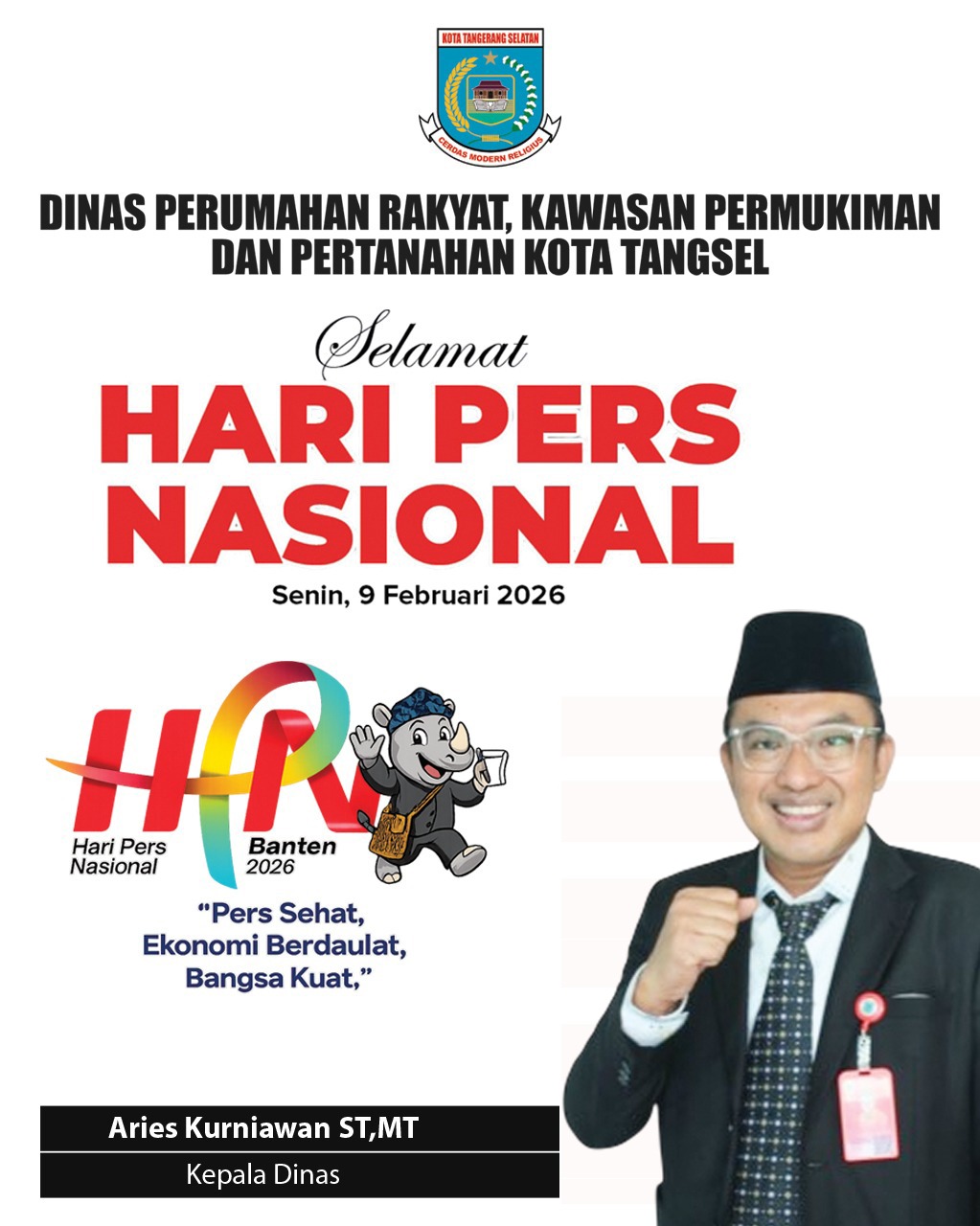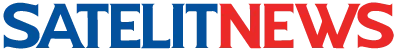Oposisi Setengah Hati

DALAM nadi demokrasi yang sehat, oposisi bukanlah musuh, melainkan mitra kritis yang menjaga agar kekuasaan tidak melaju tanpa kendali. Ia adalah suara kritis yang memastikan kebijakan tetap berpihak pada rakyat, cermin yang memantulkan kekurangan pemerintah, dan jembatan yang menyuarakan aspirasi publik di tengah gemuruh politik. Di Indonesia, dengan sistem presidensialisme multipartai sebagai kerangka bernegara, oposisi yang kredibel bukan sekadar pelengkap, tetapi keharusan mutlak untuk menjaga demokrasi tetap hidup, relevan, dan bermartabat.
Namun, realitas politik Indonesia saat ini menyingkap paradoks yang mencemaskan. Di satu sisi, kita merindukan oposisi yang mampu menjadi penyeimbang efektif, seperti yang pernah ditunjukkan PDI Perjuangan (PDIP) di era Susilo Bambang Yudhoyono. Di sisi lain, kecenderungan politik akomodasi dan koalisi gemuk di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menutup ruang gerak oposisi, menjadikannya sekadar bayang-bayang tanpa daya. Lebih ironis lagi, partai-partai yang seharusnya menjadi penyeimbang justru terjebak dalam sikap setengah hati, memilih bermain aman ketimbang mengambil peran kritis. Artikel ini menggali akar masalah oposisi setengah hati, merespons ancaman populisme yang melemahkan checks and balances, dan menawarkan visi untuk membangun sistem oposisi yang kokoh demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih jernih.
Politik, Populisme, dan Koalisi
Pemerintahan Prabowo Subianto, yang dimulai pada Oktober 2024, telah mewarnai panggung politik dengan nuansa populisme yang memikat sekaligus memecah belah. Kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan kabinet besar, dan revisi Undang-Undang TNI yang kontroversial mencerminkan pendekatan jangka pendek yang menggoda segmen masyarakat tertentu.
Namun, di balik kilau popularitas, kebijakan ini sering mengorbankan prioritas strategis seperti pendidikan, riset, dan penanganan PHK, sambil memperlebar jurang polarisasi sosial. Pendekatan ini memperkuat perpecahan dan melemahkan peran oposisi dengan membingkai kritik sebagai “gangguan” ketimbang masukan konstruktif.
Populisme membelah masyarakat menjadi dua kubu: “rakyat murni” melawan “elite korup”. Dalam konteks Indonesia, populisme ala Prabowo ditandai dengan pernyataan seperti “yang tidak mendukung (MBG) silakan keluar dari pemerintahan” atau respons antikritik seperti “ndasmu” mencerminkan sikap yang menutup ruang dialog. Alih-alih memupuk musyawarah, pemerintah menciptakan politik akomodasi yang mengesampingkan perbedaan pendapat, menjadikan oposisi sebagai musuh ketimbang mitra pengawas kebijakan. Koalisi gemuk yang menguasai 63,46 persen suara legislatif melibatkan Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, NasDem, dan PKB semakin mempersempit ruang gerak oposisi, menjadikan DPR lebih sebagai stempel kebijakan ketimbang pengawas yang kritis.
Sementara itu, PDIP yang menguasai 16,72 persen suara di parlemen, tampak terjebak dalam sikap ambivalen. Pernyataan bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi, dengan dalih filosofi gotong royong Pancasila, mencerminkan sikap setengah hati yang melemahkan potensi partai sebagai penyeimbang. Dinamika internal, termasuk kasus korupsi yang melibatkan kader, serta keputusan untuk mendukung revisi UU TNI yang kontroversial, semakin menegaskan bahwa PDIP lebih memilih kompromi ketimbang konfrontasi. PKS, dengan 8,42 persen suara, menunjukkan niat beroposisi, tetapi kapasitasnya terbatas oleh jumlah kursi yang kecil. Inilah wajah oposisi setengah hati yang kita saksikan hari ini: penuh potensi, tetapi kekurangan keberanian.
Mengapa Oposisi Kredibel Penting?
Oposisi yang kredibel bukanlah sekadar kelompok yang menolak pemerintah demi menolak. Ia adalah institusi politik yang menawarkan visi alternatif, mengawasi jalannya kekuasaan, dan memastikan akuntabilitas.
Dalam demokrasi, oposisi adalah cermin yang memantulkan kekurangan pemerintah, sekaligus jembatan yang menyuarakan aspirasi publik yang terabaikan. Tanpa oposisi yang kuat, risiko penyalahgunaan kekuasaan meningkat dan demokrasi terancam tergerus menuju otoritarianisme terselubung.
Sejarah politik Indonesia menunjukkan kekuatan oposisi yang efektif. Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014), PDIP memposisikan diri sebagai oposisi yang kritis, menyuarakan alternatif kebijakan ekonomi dan sosial yang memperkuat legitimasi partai di mata publik. Sikap ini tidak hanya memperbesar peluang PDIP memenangkan kekuasaan pada 2014, tetapi juga menunjukkan bahwa oposisi yang terstruktur mampu menjadi katalis perubahan. Sebaliknya, pengalaman Gerindra sebagai oposisi selama 2009-2019 dinilai kurang kredibel karena lebih mengandalkan sentimen populis ketimbang membangun sistem kritik yang substansial.
Kredibilitas oposisi tidak lahir dari ledakan emosi atau jargon semata, tetapi dari tiga pilar: suara yang jelas, struktur yang kokoh, dan komitmen pada demokrasi.
Suara yang jelas berarti oposisi harus mampu mengartikulasikan visi alternatif berbasis data, logika, dan kepentingan rakyat, bukan sekadar reaksi emosional. Struktur yang kokoh menuntut koordinasi internal yang kuat, kaderisasi yang menghasilkan pemimpin berkualitas, dan strategi komunikasi yang konsisten. Komitmen pada demokrasi berarti oposisi harus tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai kebangsaan, tanpa memicu polarisasi yang merusak. Sayangnya, oposisi setengah hati yang kita lihat hari ini gagal memenuhi ketiga pilar ini, terjebak antara ambisi politik jangka pendek dan ketakutan menghadapi tekanan kekuasaan.
Populisme Pedang Bermata Dua
Populisme ala Prabowo, meskipun memikat dengan janji-janji prorakyat seperti MBG, memiliki sisi gelap yang mengancam demokrasi. Kebijakan ini, meskipun tampak inklusif, sering kali mengabaikan keberlanjutan fiskal dan prioritas jangka panjang seperti pendidikan dan riset. Lebih jauh, populisme ini memicu polarisasi sosial, membelah masyarakat menjadi kubu loyalis dan skeptis.
Pernyataan antikritik dari Prabowo, seperti “ndasmu”, bukan sekadar ekspresi emosional, tetapi sinyal bahwa perbedaan pendapat dianggap tidak relevan dalam lanskap politik yang ia bangun. Media sosial memperparah situasi ini, dengan hoaks dan narasi yang memecah belah, sebagaimana terlihat pada Pemilu 2019.
Polarisasi politik dapat meningkatkan konflik sosial, menurunkan kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. Ketergantungan pada program jangka pendek dapat memicu krisis ekonomi dan sosial. Di Indonesia, populisme yang mengesampingkan musyawarah dan mengabaikan kritik berisiko menjadi bom waktu, meninggalkan beban bagi generasi mendatang.
Dalam konteks ini, oposisi yang kredibel menjadi penyeimbang yang krusial. Ia mendorong dialog konstruktif, mencegah polarisasi yang merusak dan memastikan kebijakan tidak hanya memikat, tetapi juga berkelanjutan. Namun, ketika oposisi setengah hati seperti yang ditunjukkan oleh sikap ambivalen PDIP mendominasi, ruang untuk checks and balances menyusut, membuka jalan bagi konsolidasi kekuasaan yang berpotensi otoriter.
Tantangan Oposisi Setengah Hati
Oposisi di era Prabowo menghadapi tantangan berlapis. Pertama, koalisi gemuk yang menguasai mayoritas parlemen membuat oposisi sulit bergerak. Dengan 63,46 persen suara legislatif di tangan koalisi, partai seperti PDIP dan PKS terpojok dalam dinamika politik yang didominasi akomodasi. Kedua, sikap antikritik pemerintah menciptakan suasana di mana kritik dianggap sebagai pengkhianatan, bukan bagian dari demokrasi. Ketiga, kelemahan internal partai oposisi, seperti konflik dalam PDIP dan keterbatasan kursi PKS, melemahkan kapasitas mereka untuk menjadi penyeimbang efektif. PDIP, yang seharusnya menjadi motor oposisi, justru terjebak dalam sikap setengah hati. Pernyataan bahwa PDIP tidak akan menjadi oposisi, dengan dalih filosofi gotong royong, bertentangan dengan peran partai sebagai penyeimbang.
Dukungan terhadap revisi UU TNI yang kontroversial semakin menegaskan bahwa PDIP lebih memilih kompromi ketimbang konfrontasi. PKS, meskipun menunjukkan niat beroposisi, terkendala oleh skala yang terbatas. Kondisi ini mencerminkan fenomena di mana rezim populis melemahkan oposisi melalui strategi “pecah belah, lalu kuasai”.
Membangun Oposisi Kredibel
Untuk mengatasi oposisi setengah hati, Indonesia perlu membangun sistem oposisi yang kredibel melalui langkah-langkah strategis:
Pertama, reformasi Partai Politik: PDIP dan PKS harus memperkuat struktur internal melalui kaderisasi yang menghasilkan pemimpin visioner dan visi alternatif yang jelas. PDIP, dengan sejarahnya sebagai oposisi kritis, perlu kembali ke akarnya sebagai penyeimbang yang berani, bukan pendukung pasif di parlemen.
Kedua, Pendidikan Politik Publik: Literasi politik masyarakat harus ditingkatkan untuk memahami pentingnya oposisi dalam demokrasi. Lembaga masyarakat sipil dapat memfasilitasi dialog berbasis fakta untuk meredam polarisasi.
Ketiga, media sebagai Penjaga Netralitas: Media massa harus menghindari narasi provokatif dan memfasilitasi diskusi konstruktif antara pemerintah, oposisi, dan masyarakat. Media adalah jembatan yang dapat memperkuat suara oposisi tanpa memperburuk perpecahan.
Keempat, Penguatan Institusi Demokratis: DPR, KPK, dan Mahkamah Konstitusi harus diperkuat sebagai pengawas independen. Revisi UU yang melemahkan institusi ini harus dicegah melalui tekanan publik dan legislatif.
Kelima, peran Aktif Masyarakat Sipil: LSM, akademisi, dan komunitas masyarakat perlu menciptakan ruang dialog lintas kelompok untuk mendorong kolaborasi dan meredam polarisasi. Forum-forum seperti diskusi publik atau seminar nasional dapat menjadi wadah untuk membahas isu krusial, seperti stabilitas koalisi dan reformasi birokrasi.
Menyalakan Api Demokrasi
Oposisi setengah hati adalah cerminan dari demokrasi yang terancam redup. Di tengah gemerlap populisme yang menjanjikan solusi instan, oposisi yang kredibel adalah nyala api yang menjaga demokrasi tetap hidup mengingatkan kita akan pentingnya akuntabilitas, keberlanjutan, dan keadilan. Indonesia, dengan sejarah perjuangan demokrasi yang panjang dan penuh liku, tidak boleh terjebak dalam politik akomodasi yang membungkam perbedaan. Sebaliknya, kita harus menyalakan kembali semangat untuk memperjuangkan demokrasi yang sejati, di mana suara kritis bukan ancaman, tetapi kekuatan.
Pemerintahan Prabowo Subianto memiliki peluang untuk menjadi pemerintahan yang inklusif, tetapi hanya jika ia bersedia mendengar kritik dan memperkuat checks and balances. PDIP, dengan kekuatan politiknya, memiliki tanggung jawab besar untuk keluar dari sikap setengah hati, kembali menjadi penyeimbang yang berani, dan menyuarakan aspirasi rakyat yang terpinggirkan. Masyarakat sipil, media, dan institusi demokratis lainnya harus turut serta menjaga agar demokrasi tidak tergerus oleh polarisasi dan konsolidasi kekuasaan.
Di ujung lorong yang kelam, ada harapan untuk Indonesia yang lebih demokratis di mana oposisi bukan musuh, tetapi mitra yang menjaga keseimbangan kekuasaan. Mari kita bangun oposisi yang kredibel, bukan demi perlawanan semata, tetapi demi masa depan yang adil, transparan, dan bermartabat. Karena dalam demokrasi yang sejati, perbedaan pendapat adalah denyut nadi yang membuat bangsa ini hidup, bergerak, dan terus melangkah menuju cita-cita luhur: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita nyalakan kembali api demokrasi, dengan keberanian, kearifan, dan semangat gotong royong yang sejati.(*)
*) Penulis merupakan Dosen Ilmu Pemerintahan di Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Mathla’ul Anwar Banten.
Olahraga | 2 hari yang lalu
Nasional | 1 hari yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
Pos Banten | 1 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu