Surat Terbuka yang Mendebarkan Para Sastrawan
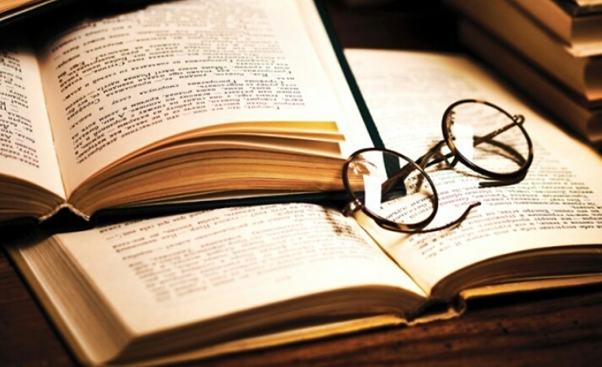
SERPONG - Dalam suatu ceramahnya di hadapan mahasiswa UI (2017), Prabowo Subianto pernah membahas secara mendetil suatu novel karya Peter Singer, “Ghost Fleet” (Armada Hantu). Dalam novel tersebut diceritakan perihal hilangnya negeri Indonesia pada 2030, diakibatkan pertemuan besar geopolitik dunia yang memperebutkan Pulau Natuna, khsusnya antara Cina dan Amerika Serikat.
Prabowo juga bicara tentang paradox Indonesia, meramal soal geoekonomi bahwa akan terjadi pertikaian kepentingan, serta perebutan proyek minyak dan gas, yang membuat Indonesia lagi-lagi hanya akan terkena gatah dan imbasnya. Namun demikian, Prabowo tidak membahas tanggapan Peter Singer melalui akun twitter-nya, bahwa ia pernah menegaskan novelnya adalah karya fiksi yang terilhami dari tren kemajuan teknologi saat ini, bukan merupakan prediksi atau ramalan pasti.
Terlepas dari pembahasan soal prediksi masa depan yang menjadi legitimasi kepentingan politik, saya ingin mengungkap perihal karakter alam bawah sadar manusia Indonesia, termasuk para penulis dan sastrawannya, yang begitu mudah tersusupi oleh suatu mitos, dogma, maupun karya-karya fiksi buatan “orang asing”. Beberapa tahun lalu, saya juga masih ingat dalam suatu acara pertemuan sastra di kaki Candi Borobudur, Magelang, yang membahas tentang karya sastra berlatar setting di zaman kerajaan Majapahit (Gajah Mada). Saat itu, beberapa penulis yang menyebut dirinya ‘novelis sejarah’ menyerang dan memaki-maki karya Damar Sasongko yang pernah mengambil referensi dari Klenteng Sam Poo Kong, serta menyebut Nyo Lai Wa sebagai salah seorang raja Majapahit.
Saat itu, tampak sekali beberapa novelis sejarah (yang tak perlu disebutkan namanya) seakan menilai Damar sebagai seniman yang pantas dikriminalisasi. Caci-maki berhamburan, ditujukan kepada editornya yang hadir pada saat itu. Sebagian dari mereka tersenyum, beberapa dari mereka tertawa terbahak-bahak. Yang terpikir oleh saya, bukankah Damar itu hanya menulis sebuah karya fiksi yang sah-sah saja mengambil dari rujukan manapun sebagai sumber datanya. Damar tak pernah menyatakan dirinya sebagai ‘sejarawan’ yang memang bekerja berdasarkan fakta dan data yang akurat.
Pada momen tersebut, terasa nuansa mistik bertaburan takhayul, terutama pada kalangan seniman tua yang terus saja mengepulkan asap rokoknya. Barangkali nuansa macam itulah yang menjadi sorotan Nirwan Dewanto melalui gugatan dalam surat terbukanya yang ditujukan kepada Kurator Panduan Buku Sastra. Tarik-menarik kepentingan senior dan yunior, dominasi penulis lama ketimbang pendatang baru, hingga ke soal perebutan kekuasaan untuk mendominasi pengaruh mereka di dunia penerbitan dan media massa. Kini, semuanya itu telah terhempas oleh beberapa lembar surat terbuka yang kian marak menjadi perdebatan publik.
Hal ini mengingatkan saya pada pernyataan bersayap dari mendiang Buya Syafii Maarif (1935-2022), perihal banyaknya topeng dan kepalsuan pada wajah-wajah budayawan dan sejarawan kita. Kemerdekaan jiwa tidak menampak pada goresan pena mereka. Ini menjadi permisifisme yang secara sosial akan membentuk karakter orang-orang waras di negeri ini, yakni mereka yang tidak ingin terlibat terlalu jauh dalam persoalan remeh-temeh yang ditimbulkan oleh politik dan kekuasaan. Sebab, orang waras semacam Nirwan Dewanto adalah wujud rasionalitas publik yang berani menghadapi segala absurditas dan ketakrasionalan para manipulator yang oligarkis di bidang penerbitan buku sastra.
Kewarasan pemikiran Nirwan Dewanto akan tetap terjaga dengan baik, terlebih di saat negeri ini dilanda situasi dan kondisi yang penuh kegilaan, stres, dan depresi masal. Dengan loyalitas dan ketulusannya pada nilai-nilai kemanusiaan, Nirwan punya caranya sendiri untuk melakukan apa yang bisa dilakukan meskipun dalam kondisi terbatas. Hal ini disebabkan, negara dan pemerintah seringkali absen saat rakyat marjinal membutuhkan perannya, lantaran direpotkan oleh urusan politik praktis, birokrasi yang tidak efisien, kasus hukum yang tak berujung-pangkal, serta disibukkan oleh pemikiran-pemikiran dangkal dan sempit belaka.
Bila kita mencermati kedalaman makna dari cerpen “Jimat dari Mayor Gibran” (Koran Tempo), kita memahami keagungan karya sastra yang membahas karakteristik dan memori kolektif orang Indonesia masa kini. Karya sastra yang dihasilkan dari ketekunan dan totalitas imajinasi seperti itu, sekaligus mengandung impian dan harapan tentang keadilan, pergaulan hidup yang baik, dan bukan hanya retorika omongan politik yang menjemukan.
Karya sastra yang baik niscaya menciptakan ruang dalam tubuh yang membuat seseorang atau suatu masyarakat bisa menerima perbedaan dengan bijak dan rendah-hati. Ada perspektif atau sudut pandang filosofis yang mengungkap nilai-nilai kehidupan manusia. Kita dapat menengok dan membaca sistem nilai yang bersifat personal maupun sosial. Di dalamnya ada himpunan atau bunga rampai mengenai harapan dan tragedi manusia, baik tentang makna kehidupan yang baik maupun buruk, benar maupun salah, bahkan indah maupun jelek.
Cerpen lain yang tak kalah heboh di ranah publik akhir-akhir ini adalah “Sebatang Pohon yang Ditanam Menjelang Kiamat”. Setiap karya sastra yang baik selalu mengajak kita saling membuka wawasan dan cakrawala agar mengadakan introspeksi dan bercermin diri. Menurut Nirwan Dewanto, karya sastra sebagai suatu bentuk komunikasi yang elegan, akan selalu menjadi ruang bagi penggambaran dan pewartaan sistem bermasyarakat yang baik, yang juga meliputi sistem hukum, agama hingga tata negara yang berkeadilan.
Ada semacam tanggung jawab dalam pribadi Nirwan melalui surat terbukanya. Ia menilai karya sastra tidak pantas hanya menjadi bantal pelukan dan kasur empuk bagi kaum pengkhayal dan pemimpi. Ia akan mengubah situasi-kondisi melalui ruang tafsir yang menjadi watak dari kekuatan plot yang dinarasikan oleh para sastrawan.
Bagi seorang Nirwan, sejarah dan otokritik dalam kandungan sastra selalu menjadi inheren. Di dalamnya ada nuansa sejarah yang senantiasa berpijak di atas bumi, dengan gapaian tentang ruang langit yang bersifat ilahiah. Di situlah ruang sastra akan memberikan keseimbangan, karena ia memiliki dimensi horisontal sekaligus vertikal. Ia juga mengandung makna dan tafsir tentang gapaian keilahian dalam rentang jalan lurus ke ufuk perjumpaan.
Sastra dan perjumpaan dengan yang transenden merupakan fenomena pencarian bersinambungan yang tiada akhir. Itulah yang tergores dalam bait-bait puisi Nirwan, semisal “Lazar” atau “Tulisan pada Nisan”. Bagi Nirwan, selayaknya tiap-tiap sastrawan memahami dan mendalami sejarah sosial bangsanya sendiri, sebelum ia banyak berkutat dalam urusan sosial bangsa di negeri-negeri lain (wong liyan). Mereka harus berusaha melacak tatanan nilai lingkungan, serta memahami kondisi manusia Indonesia, baik secara psikologis maupun antropologis.
Ruang dialog menjadi keniscayaan setelah Surat Terbuka menyatakan penolakan atas karya-karya puisinya untuk dilibatkan dalam “Kurikulum Merdeka” yang justru masih terbelenggu. Ruang dialog seakan dipertaruhkan dalam kerangka karya sastra yang bergerak dinamis, untuk menggapai relung-relung jiwa dan kalbu manusia. Melalui ruang itulah gapaian kepada keilahian selalu menggetarkan, bahkan menciptakan oleng-kemoleng keyakinan karena pertemuan dengan persilangan horisontal, yang kian menyebabkan limbungnya keseimbangan para sastrawan kita (baca: Sastra, Takhayul dan Kebuntuan Ideologis, kompas.id).
Meskipun bergelut dengan hal-hal yang bersifat mistisisme, bagaimanapun dunia sastra memiliki citra dan kekhasannya tersendiri. Ia memiliki karakter berbeda dengan petuah agama maupun kitab suci yang bersifat tekstual. Ia mengandung penafsiran akan makna-makna alamiah (kauniyah) yang diikhtiarkan dari kecerdasan sastrawan, hingga sanggup membaca dan menangkap apa yang dimaui Tuhan sebagai Sang Pencipta atau Sang Kreator yang sesungguhnya.
Kita mengenal pengakuan sastrawan muslim, Muhamad Iqbal (Pakistan), ketika ia mendalami pemikiran filosofis dari Nietszche (Eropa). Keyakinan spiritual Iqbal seakan terguncang dahsyat. Tetapi, justru lantaran itu ia semakin menemukan keyakinan baru yang lebih kokoh mengakar, sebagai sosok sastrawan dengan pemikirannya yang multidimensional. Iqbal yang cenderung eksklusif, akhirnya menemukan inklusivitasnya, hingga sanggup berdialog dengan berbagai macam keyakinan, sastra dan religiusitas, hingga agama-agama dunia (baca: Sastra dan Religiositas Muhammad Iqbal, litera.co.id)
Bagi saya selaku sarjana Sastra, Nirwan Dewanto yang tercermin jelas melalui surat terbukanya itu, adalah sosok sastrawan yang genuine. Tidak ada benih-benih dialog yang dangkal, banal dan urakan, yang seringkali memunculkan kegaduhan dan bias keributan semata. Mari kita sikapi pernyataan yang jujur itu dengan kecerdasan dan kedewasaan sebagai penulis dan sastrawan yang merdeka, melampaui keakuannya, juga telah selesai dengan dirinya. Bukan dengan sikap sastrawan yang selama ini dijuluki sebagai pendendam dan pendengki semata.
Pos Tangerang | 2 hari yang lalu
SEA Games 2025 | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
TangselCity | 2 hari yang lalu
SEA Games 2025 | 2 hari yang lalu
SEA Games 2025 | 20 jam yang lalu
Olahraga | 2 hari yang lalu
SEA Games 2025 | 1 hari yang lalu
Pendidikan | 2 hari yang lalu
TangselCity | 1 hari yang lalu






















